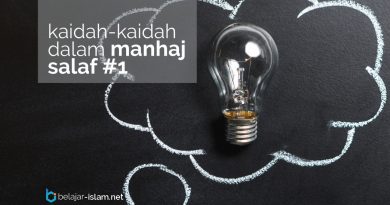BEBERAPA KAIDAH DALAM MANHAJ SALAF #2
Oleh: Syaikh DR. Abdussalam bin Salim as-Suhaimi
Kaidah keempat:
إِنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح
“Sesungguhnya menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan (manfaat).”
Dalil kaidah ini adalah:
1. Firman Allah ta’ala:
وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ
“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. Al-An’am [6]:108)
Allah mengharamkan memaki sembahan-sembahan orang-orang musyrik, padahal memaki sembahan mereka termasuk marah karena Allah dan merendahkan karena Allah serta sebagai bentuk penghinaan kepada sembahan-sembahan mereka. Hal itu dilarang karena dapat menjadi alasan bagi mereka untuk memaki Allah ta’ala. Maka manfaat menghilangkan cacian terhadap Allah lebih besar daripada manfaat yang kita dapatkan dari mencaci sembahan-sembahan mereka.
2. Disebutkan dalam hadits A’isyah, sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
يَا عَاِئشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيْثُوْا عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيْهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ
“Wahai ‘Aisyah, seandainya bukan karena suku bangsamu baru saja meninggalkan masa jahiliah, niscaya aku akan memerintahkan agar baitullah dirobohkan, lalu aku akan memasukkan apa yang telah dikeluarkan darinya, kemudian aku akan meratakannya dengan tanah.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Dalam hadits ini terdapat dalil yang jelas, yang menunjukkan makna kaidah di atas. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam meninggalkan kemaslahatan membangun kembali Al-Baitul ‘Atiiq (Ka’bah) berdasarkan dasar bangunan (fondasi) Ibrahhim ‘Alaihissalaam karena untuk menghindari mafsadat (keburukan) yang dikhawatirkan terjadi apabila Ka’bah tetap dihancurkan lalu dibangun kembali. Keburukan itu adalah manusia akan membeci Islam atau mereka akan murtad disebabkan penghancuran Ka’bah. Oleh karena itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendahulukan mencegah mafsadat ini daripada mengambil maslahat.
3. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak membunuh orang-orang munafik, padahal membunuh mereka adalah kemaslahatan. Namun Nabi meninggalkannya agar tidak membuat manusia benci (terhadap Islam) dan untuk menghindari tuduhan bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam membunuh sahabatnya sendiri.
4. Larangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membunuh para penguasa dan memberontak kepada mereka, walaupun mereka zalim, selama mereka masih menegakkan shalat, dalam rangka menutup sebab munculnya kerusakan yang besar dan keburukan yang banyak. Karena realita menunjukkan bahwa penyerangan dan pemberontakkan terhadap penguasa menyebabkan kemungkaran yang lebih berlipat-lipat daripada kemungkaran sebelumnya. Sampai saat ini umat masih berada dalam sisa-sisa kerusakan itu.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
إِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتٌلُوْا الْآخِرَ مِنْهُمَا
“Jika ada dua khalifah yang dibai’at, maka bunuhlah khalifah yang paling terakhir dari keduanya.”(HR. Muslim)
Hal demikian dilakukan dalam rangka menutup jalan keburukan. Demikian diringkas dari penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
Setelah menyebutkan sejumlah cabang yang termasuk dalam kaidah:
دَرْءُ الْمَفَاسِد أَوْلَى عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح
“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan (manfaat).” Dan kaidah:
إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَصَالِحُ وَالْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَرْجَحُ مِنْهُمَا عَلَى الْمَرْجُوْحِ
“Jika maslahat dan mafsadat bertubrukan maka yang lebih unggul (kuat, dominan) dari keduanya didahulukan daripada yang ringan (sedikit).”
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:
“Sesungguhnya di antara prinsip Ahlussunnah wal Jama’ah adalah tetap bersama Al-Jama’ah (orang-orang yang taat kepada penguasa muslim) dan tidak memerangi para penguasa -yakni penguasa yang zalim- dan tidak ikut serta dalam peperangan di zaman fitnah, semua ini masuk ke dalam kaidah umum:
Apabila maslahat dan mafsadat bertubrukan, kebaikan dan keburukan berlanggaran atau berdesak-desakan, maka wajib mendahulukan yang dominan dari keduanya.
Tatkala maslahat dan mafsadat berdesak-desakan dan saling bertubrukan, maka dalam amar makruf nahi mungkar, baik yang bertujuan untuk meraih maslahat ataupun menolak mafsadat, harus mempertimbangkan lawannya. Apabila maslahat yang luput lebih banyak atau mafsadat yang muncul lebih besar; maka amar makruf nahi mungkar tidak diperintahkan, bahkan diharamkan jika mafsadat lebih banyak daripada maslahatnya.
Kadar maslahat dan mafsadat ditimbang dengan timbangan syar’i. Berdasarkan hal itu, maka jika seseorang atau kelompok dilema (sulit menentukan pilihan) antara kebaikan dan keburukan, saat di mana mereka tidak dapat menentukan pilihan di antara keduanya, apakah mereka harus melakukan keduanya atau meninggalkan keduanya; maka mereka tidak boleh melakukan amar makruf dan juga tidak boleh melakukan nahi mungkar. Akan tetapi dia harus mempertimbangkan, jika kebaikan yang dihasilkan lebih besar maka ia boleh melakukan amar makruf, walaupun mengakibatkan kemungkaran yang lebih kecil.
Maka tidak boleh melakukan nahi mungkar jika mengakibatkan kehilangan kebaikan yang lebih besar; karena nahi mungkar dalam keadaan seperti itu termasuk perbuatan menghalangi dari jalan Allah dan perbuatan menghilangkan ketaatan terhadap Allah dan terhadap Rasul-Nya, serta termasuk usaha menghilangkan perbuatan baik.
Jika kemungkaran lebih mendominasi, maka ia harus melakukan nahi mungkar walaupun menyebabkan kehilangan kebaikan yang lebih kecil. Maka melakukan amar makruf yang menyebabkan lahirnya kemungkaran yang lebih banyak daripada sebelumnya adalah termasuk kemungkaran, serta termasuk perbuatan maksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya.
Adapun jika kebaikan dan kemungkaran yang serentak (terjadi atau berlaku pada waktu yang bersamaan) itu setara, maka tidak boleh melakukan amar makruf nahi mungkar. Terkadang yang tepat adalah amar makruf, namun terkadang nahi mungkar lebih tepat, kadang kala amar makruf dan nahi mungkar keduanya tidak tepat dilakukan, karena kebaikan dan kemungkaran itu saling bertalian (simultan, berbarengan), namun hal seperti ini bersifat kasuistik (situasional).
Adapun menurut jenisnya, maka seseorang diajak kepada kebaikan secara mutlak dan dilarang dari kemungkaran secara mutlak. Seorang pelaku ataupun suatu kelompok, maka harus diajak kepada kebaikan dan dilarang dari kemungkaran, kebaikannya dipuji dan keburukannya dicela. Asalkan amar makruf tidak menyebabkan hilangnya kebaikan yang lebih banyak atau tidak menyebabkan keburukan yang lebih besar. Dan selagi nahi mungkar tidak menyebabkan lahirnya kemungkaran yang lebih besar atau tidak menyebabkan hilangnya kebaikan yang lebih banyak.
Dan termasuk bab ini (Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan) adalah: penerimaan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam atas Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang serupa dengannya dari kalangan tokoh-tokoh munafik dan para pendosa; karena para tokoh ini memiliki para pendukung, maka menghilangkan kemungkarannya dengan suatu hukuman akan menyebabkan hilangnya kebaikan yang lebih banyak, di antara keburukan itu adalah dapat menyebabkan kemurkaan kaumnya dan para pendukungnya, juga akan menyebakan manusia benci (terhadap Islam) saat mereka mendengar bahwa Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam membunuh sahabat-sahabatnya.” (dari penjelasan Syaikhul Islam dalam kitab: Majmuu’ Al-Fataawa(28/128-131) dan kitab: Al-Amru Bil Ma’ruuf Wan Nahyu ‘Anil Munkar, karya Syaikhul Islam (hal. 21))
Kaidah kelima:
أَنَّ الْأَحْكَامَ الْأُصُوْلِيَّةّ وَالْفُرُوْعِيَّةَ لَا تَتِمُّ إِلاّ بَأَمْرَيْنِ هُمَا: وُجُوْدُ الشَّرُوْطِ وَانْتِفَاءُ الْمَوَانِع
“Sesungguhnya hukum-hukum dalam ushul (pokok) dan furu’ (cabang) tidak sempurna kecuali dengan dua hal berikut: terpenuhinya syarat dan tidak adanya penghalang.” (Syarh Al-Qawaa’id As-Sa’diyyah (hal. 89))
Aku katakan: ini adalah kaidah yang penting dalam semua hukum-hukum syar’i, baik dalam pokok agama ataupun cabangnya, wajib terpenuhi syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Walupun syarat terpenuhi tapi jika masih ada suatu penghalang, maka hukum tidak sah. Contohnya: ayat-ayat ancaman bagi orang yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan, sebetulnya pelaku dosa itu terancam dengan apa yang terkandung dalam dalil, hanya saja terkadang ada suatu penghalang yang menghalanginya dari azab, seperti taubat, permohonan ampun dari orang-orang mukmin, musibah-musibah (dari sumber yang sama dengan sebelumnya, pada halaman yang sama) atau hal-hal lainnya yang dapat menggugurkan dosa.
Contoh lainnya: shalat itu harus dipenuhi syaratnya, yaitu thaharah, jika seseorang ingin shalat tanpa thaharah, maka shalatnya tidak sah; karena tidak memenuhi syaratnya.
Termasuk cakupan kaidah ini adalah: mengkafirkan pelaku kekafiran (takfiir) memvonis seseorang sebagai mubtadi’ (pelaku bid’ah) dan memvonis pelaku kefasikan sebagai orang fasik (tafsiiq) (ini adalah pembahasan yang di dalamnya terdapat banyak kekacauan, keributan, kesembronoan dan perpecahan. Juga banyak terdapat hawa nafsu serta pendapat yang berbeda-beda). (lihat kitab: Mauqif Ahlis Sunnah wal Jamaa’ah min Ahlil Ahwa-i wal Bida’i (1/237)
Sikap Ahlussunnah wal Jamaa’ah yang meniti manhaj As-Salaf Ash-Shalih dalam mengkafirkan ahli bid’ah dan orang yang memiliki akidah yang menyimpang adalah memerinci1 , karena para ahli bid’ah tidak berada dalam derajat yang sama:
a. Di antara mereka ada yang dihukumi kafir, seperti orang yang mengucapkan perkataan yang mengkafirkan atau melakukan perbuatan yang mengkafirkan, itupun jika telah memenuhi syarat untuk dihukumi kafir dan tidak ada penghalang jatuhnya hukum itu.
b. Di antara mereka ada pula yang tidak dihukumi kafir (walaupun mengucapkan perkataan kufur atau melakukan perbuatan kufur) karena ia tidak memenuhi syarat untuk dihukumi kafir dan padanya masih terdapat penghalang hukum itu2.
Dengan demikian, maka pengkafiran ahli bid’ah dan pengkafiran secara umum adalah berlandaskan kepada dua kaidah yang penting berikut:
1. Adanya dalil dari kitab dan sunnah yang menunjukkan bahwa perkataan atau perbuatan yang muncul dari orang yang duhukumi itu menuntut adanya pengkafiran.
2. Berlakunya hukum ini bagi orang tertentu yang mengucapkan atau melakukukan kekufuran itu, dengan terpenuhinya syarat dan tidak adanya penghalang3.
Dua kaidah ini juga berlaku bagi seseorang yang akan divonis sebagai mubtadi’ (pelaku bid’ah) dan orang fasik, yaitu harus ada dalil dari kitab dan sunnah yang menunjukkan bahwa ucapan dan perbuatannya itu adalah bid’ah, dan orang yang mengucapkan atau melakukan bid’ah itu telah memenuhi syarat untuk divonis, serta tidak ada penghalang-penghalang padanya4. Allahu a’lam (Allah lebih mengetahui)
Diterjemahkan oleh Ustadz Hafizh Abdul Rohman, Lc. (Abu Ayman) dari kitab:
Kun Salafiyyan ‘Alal Jaaddah, ‘Abdussalaam bin Saalim bin Rajaa As-Suhaimi, Ad-Daarul Atsariyyah, 2012 M
________________________________________________________________________________
Footnote:
[1] Ada pendapat yang mengingkari takfir secara total, menurut mereka tidak seorang pun dari ahli kiblat boleh dikafirkan, ada pula pendapat yang mengkafirkan ahli bid’ah secara mutlak (tanpa merinci), menurut mereka ahli bid’ah itu semuanya kafir, keluar dari Islam. Kedua pendapat ini jauh dari kebenaran, bertentangan dengan dalil-dalil syar’i. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah menyebutkan kelirunya orang yang menisbatkan dua pendapat ini kepada salah seorang dari Imam-imam salaf, dan bahwa yang benar adalah melakukan perincian, itulah pendapat yang benar dari para Imam salaf. Lihat: Majmuu’ Al-Fataawaa (7/337-340)
[2, 3, 4] Lihat Majmuu’ Al-Fataawaa (3/352-354, 12/497, 498), Syarh Al-Aqiidah Ath-Thahaawiyyah (338-3340) dan lihat pembahasan lengkap tentang masalah ini dalam kitab: Mauqif Ahlis Sunnah wal Jamaa’ah min Ahlil Ahwaa-I wal Bida’I, karya saudara yang terhormat Syaikh, Doktor Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili (1/163-235)